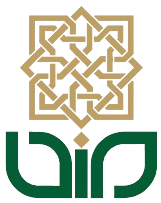Belakangan ini, kasus korupsi kembali terkuak. Sebenarnya, ini bukan hal baru, bahkan seolah telah menjadi ritual rutin yang terus berulang. Namun, ada anomali yang mengusik akal sehat dan memancing rasa heran atau bahkan amarah publik: wajah-wajah para tersangka itu.
Respons para tersangka tersebut berbeda-beda. Sebagian tertunduk menutupi wajah karena malu, sementara yang lain justru tersenyum lebar dan melambaikan tangan bak selebritas. Namun, di balik kontradiksi ini tersimpan satu kesamaan: nihilnya rasa bersalah, tidak minta maaf dan malah minta dimaafkan. Mereka mungkin meratapi hilangnya gengsi atau justru tak peduli sama sekali, tapi tak satu pun menunjukkan penyesalan karena mengkhianati amanah rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita hanya berkutat pada shame culture (budaya malu) yang rapuh dan kehilangan guilt culture (budaya rasa bersalah).
Untuk memahami fenomena ganjil ini, kita perlu meniliki gagasan antropolog Ruth Benedict tentang dua kutub moralitas: guilt culture dan shame culture. Perbedaannya sederhana namun mendasar: di mana letak kompas moral kita?
Dalam budaya rasa bersalah, kompas itu bersemayam di dalam hati nurani. Seseorang akan merasa tersiksa jika mencuri uang rakyat, meskipun tidak ada KPK yang menyadap atau CCTV yang merekam. Sanksinya internal; ia tak bisa tidur nyenyak karena dihantui dosanya sendiri.
Sebaliknya, bangsa kita tampaknya lebih memeluk budaya malu. Di sini, standar moral ditentukan oleh mata orang lain. Seseorang tidak merasa bersalah karena korupsi; ia baru merasa hancur jika ketahuan. Absennya nurani inilah yang menjelaskan mengapa sebagian koruptor masih bisa tersenyum lebar. Dalam shame culture, tertangkap OTT bukanlah momen pertobatan moral, melainkan sekadar momen jatuh gengsi atau sedang apes. Senyum dan lambaian tangan itu adalah sinyal bahwa meski tertangkap, mereka merasa masih memiliki kuasa.
Di sinilah letak celah fatalnya. OTT sejatinya hanyalah instrumen kejut yang bermain di ranah eksternal. Ia memang efektif memicu rasa malu, namun efeknya sering kali hanya seumur jagung—hanya ampuh selama ada sorotan kamera dan tatapan publik. Masalahnya, rasa malu itu parasit; ia bergantung sepenuhnya pada keberadaan penonton. Begitu pengawasan melonggar, rasa malu pun pudar. Ini sangat berbeda dengan budaya rasa bersalah yang bekerja bak kompas moral inheren; sebuah alarm yang terus berdering nyaring di dalam nurani, ada atau tidak ada yang melihat.
Oleh karena itu, kita tidak bisa selamanya menggantungkan harapan pada pengawas eksternal seperti KPK semata. Mustahil bagi aparat untuk memantau gerak-gerik setiap pejabat selama 24 jam non-stop. Sesungguhnya, aparat penegak hukum yang paling efektif adalah nurani yang bersemayam dalam diri sendiri.
Namun, nurani itu butuh latihan. Selama narasi pendidikan kita masih berbunyi “jangan melanggar aturan nanti ditangkap polisi”—alih-alih “jangan melanggar karena itu merugikan orang lain”—maka nurani kita akan tetap tertidur pulas. Jika pola pikir ini tak diubah, jangan kaget jika korupsi tak pernah mati. Tanpa budaya rasa bersalah, rompi oranye KPK hanyalah kostum panggung sandiwara yang silih berganti pemainnya, tanpa pernah mengakhiri ceritanya.
Renungan Ibnu Khaldun berabad silam rasanya relevan untuk menggugah kesadaran kita: “Mentalitas yang terbentuk dari kemewahan adalah sumber kehancuran. Sejatinya, nilai seorang manusia ada pada usahanya mengejar kebaikan dan mencegah keburukan, serta kelurusan wataknya dalam menjalani proses itu.” Korupsi, dengan demikian, bukan sekadar tindak pidana, melainkan bukti hilangnya nilai kemanusiaan demi mengejar kemewahan semu.
Untuk melawan godaan kemewahan semu yang disebut Ibnu Khaldun itu, kita butuh benteng nurani. Lantas, bagaimana menanam kembali benih nurani itu? Transformasi harus dimulai dari pendidikan yang bergeser dari sekadar kepatuhan aturan menuju kepekaan empati. Anak-anak harus dilatih membayangkan penderitaan orang lain akibat kecurangannya, bukan sekadar takut dihukum. Tanpa empati, korupsi hanya dianggap nominal uang, bukan kejahatan kemanusiaan.
Di sisi lain, elit politik wajib menormalisasi budaya mundur. Tak perlu menunggu rompi oranye; pejabat yang merasa gagal memegang amanah mestinya lapang dada melepaskan jabatan. Langkah ksatria ini krusial untuk menaikkan standar moral publik: mengubah mentalitas takut tertangkap menjadi takut mengkhianati kepercayaan rakyat. (Tulisan ini sudah terbit do media Cetask KR tgl 23 Januari 2026)