Gonggongan Anjing, Hanyalah Qiyasi
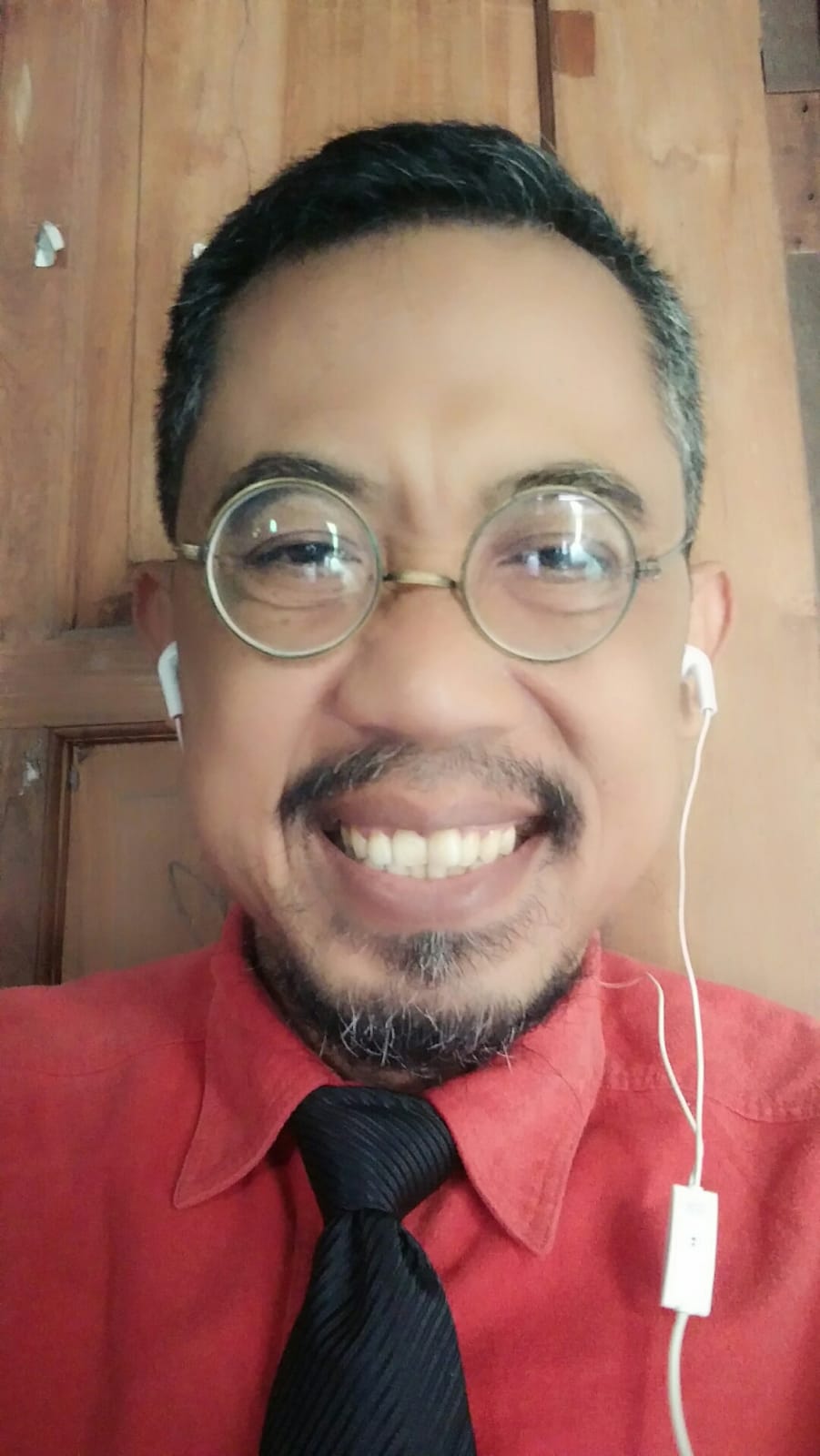
Oleh: Dr. Munawar Ahmad (Dosen Sosiologi Politik, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam)
Polemik tentang “gonggongan anjing” mencuat, bahkan menjadi viral di media sosial di bawah tagar #adzanmenag. Hal tersebut dipicu oleh cuplikan berita saat Menteri Agama, di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau, Rabu (23/2) merespons pertanyaan pewarta soal Surat Edaran (SE) Menag yang mengatur penggunaan toa di masjid dan mushola menjelaskan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama. Pada saat itu, Menteri Agama mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Menteri Agama menyatakan aturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Sebab menurutnya, Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap daerah sekitar 100-200 meter terdapat masjid atau mushola.
Berikut kutipan pernyataan lengkap Menag terkait edaran Menag soal penggunaan toa di masjid dan mushola yang belakangan ini menuai kontroversi (CNN Indonesia (20/02/2022) dalam judul "Pernyataan Lengkap Menteri Agama Yaqut soal Azan dan Gonggongan Anjing), sebagai berikut
"Iya itu kemarin kita terbitkan edaran pengaturan. Kita tak melarang masjid mushola gunakan toa, tidak. Karena itu bagian syiar Agama Islam. Tapi ini harus diatur bagaimana volume speakernya. Toanya nggak boleh kencang-kencang, 100 db. Diatur bagaimana kapan mereka gunakan speaker itu sebelum Adzan, setelah Azan. Ini tak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata agar masyarakat kita makin harmonis. Menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Kita tahu di wilayah mayoritas muslim, hampir tiap 100-200 meter ada mushola dan masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka nyalakan toanya di atas kaya apa? Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita muslim, lalu hidup di lingkungan non muslim, lalu rumah ibadah saudara kita nonmuslim bunyikan toa sehari lima kali dengan kencang-kencang secara bersamaan itu rasanya bagaimana. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini dalam satu kompleks, misalnya, kanan kiri depan belakang pelihara anjing semuanya, misalnya, menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu enggak? Apapun suara itu kita atur agar tak jadi gangguan. Speaker di mushola masjid monggo silakan dipakai, tapi diatur agar tak ada merasa terganggu. Agar niat penggunaan toa dan speaker sebagai sarana dan wasilah lakukan syiar bisa dilaksanakan tanpa mengganggu mereka yang tak sama dengan keyakinan kita.
Saya kira dukungan juga banyak atas hal ini. Karena alam bawah sadar kita mengakui pasti merasakan bagaimana suara bila tak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian ada truk kiri kanan belakang kita, mereka menyalakan mesin bersama-sama kita pasti mengganggu. Suara-suara yang tak diatur itu pasti jadi gangguan buat kita. Gitu, ya."
Gus Menteri ini adalah putra pesantren, yang kental dengan epistemologi pesantren. Beliau putra dari KH Muhammad Cholil Bisri, pengasuh di Pesantren Raudlatut Thalibin sehingga wafatnya, dan cucu dari ulama besar KH Bisri Mustofa bin H Zaenal Mustofa dan Nyai Hj Ma’rufah binti KH Cholil Harun Kasingan, Rembang. Latar belakang inilah yang menurut saya, menjadi konstruksi cara menalar Gus Menteri saat memberi qiyasi/perumpamaan tentang suara yang mengganggu, yakni nalar qiyasi/analogi
Dalam epistemologi pesantren, qiyas berarti mengira-ngirakan atau mengumpamakan. Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau mengumpamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah mengumpamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. (Adeng Septi Irawan (2021), mengutip pendapat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih terj. Saefullah Ma’shum dkk., cet. XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal 336).
Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan penalaran analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara menyandingkan berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya.
UIN Sunan Kalijaga, sebagai kampus yang mengkaji dan menerapkan epistemologi kaum pesantren, dapat dipahami jika “gonggongan anjing” hanyalah pernyataan qiyasi melalui fakta terdekat di masyarakat tentang ketidaknyamanan akibat suara bising. Suara bising inilah yang menjadi inti yang ingin disampaikan Menteri Agama, bukan tujuan menistakan adzan dengan menyamakan, mensejajarkan, atau menganggap suara adzan sama dengan gonggongan anjing, ini keliru dan inilah yang di-roasting hingga memicu kegaduhan media sosial.
Sedangkan dalam ilmu logika, nalar menggunakan perumpamaan/qiyasi disebut dengan analogi, Bernard Walliser (2019) menuliskan Reasoning by Analogy, menjelaskan jika analogi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus yang berbeda dengan cara membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi memiliki peristiwa-dalam yang identic, guna memperkuat kesimpulan, atau menegaskan kembali betapa pentingnya sesuatu tersebut.
Dengan demikian, nalar analogi Menteri Agama tersebut, yakni menautkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala, sebagai hukum/aturan yang sudah pasti, kelanjutan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978, dengan fakta lain, yakni kebisingan gonggongan anjing, sebagai kontek dengan sifat yang sama, guna memudahkan menjelaskan hal inti yang diatur oleh SE tersebut, Menteri Agama memakai contoh pada suara yang tidak nyaman dengan kisah gonggongan anjing, fakta kehidupan yang terdekat dengan kehidupan masyarakat awam. Kedua fakta tersebut dianalogikan, bukan pada subjeknya, suara adzan dan gonggongan anjing, karena antara suara adzan dan gonggongan anjing dua hal yang berlainan, tetapi analoginya pada konteks sosial dan sifatnya yakni suara yang mengganggu. inilah yang menjadi ilat dari hadirnya SE tersebut.
Nah, disinilah persoalannya, bagi yang tidak smart dalam analogi, akan terjebak pada logical fallacy, apalagi digelontori dengan informasi yang emotif-sentiment, sehingga membakar emosi masyarakat yang “tergesa-gesa-nya” pada opini penistaan agama bahwa suara adzan sama dengan gonggongan anjing. Inilah yang terjadi saat ini.
Dalam ilmu logika, memang diakui, jika penalaran analogi tersebut mempunyai sisi yang menyebabkan kesalahan penyimpulan, yakni. Pertama, tergesa-gesa, yaitu terlalu cepat menarik konklusi, sedang fakta-fakta yang dijadikan dasarnya tidak cukup mendukung konklusi itu dan sensitif. Kedua, kecerobohan, kesimpulan yang ceroboh terjadi karena mengabaikan adanya faktor-faktor analogi yang penting, yakni terjebak pada subjek bukan pada konteks. Ketiga, prasangka, prasangka membuat orang tidak mengindahkan fakta-fakta yang tidak cocok dengan konklusi. Keempat, memaksa, menjadikan ide agar terlihat benar dengan cara membandingkannya dengan ide lain yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan dengan ide yang pertama tadi.
Akhirnya, sebagai catatan kritis, melihat respon yang cepat dan cenderung emosional atas “Suara Adzan” ini mencerminkan sebuah “Tes qiyasi di ruang politik”, guna intropeksi diri atas tingkat kecerdasan ber-qiyasi-tanpa prasangka kita dalam ruang moderasi. Pada titik inilah Menteri Agama menempatkan posisi sebagai penegak suasana moderasi di Indonesia, jadi jika polemik ini berujung lebih jauh dari maksudnya, artinya kita sedang menempatkan diri pada tingkat kecerdasan beragama sekaligus sikap bermoderasi kita yang rendah, sudah layakkah Indonesia mempertahankan diri sebagai negara santun?
