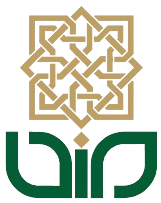Wacana dan tindakan Amerika Serikat (AS) yang mengarah pada upaya penangkapan atau kriminalisasi Presiden Venezuela dapat dipahami bukan sekadar sebagai penegakan hukum internasional, melainkan sebagai test case sekaligus bentuk “ketagihan kekuasaan” (power addiction) dalam praktik politik global. Fenomena ini menunjukkan pola berulang: ketika tindakan serupa dilakukan terhadap Irak dan Libya tanpa perlawanan berarti dari negara lain maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tindakan tersebut kemudian dinormalisasi dan direplikasi terhadap negara lain yang dianggap “menyimpang” dari kepentingan hegemon.
Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui realisme dan neorealisme dalam hubungan internasional. Dalam perspektif realis, sistem internasional bersifat anarkis, tanpa otoritas tertinggi yang benar-benar mampu mengendalikan negara-negara kuat. Negara hegemon, seperti AS, akan menggunakan seluruh instrumen—militer, hukum, ekonomi, dan diplomasi—untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Ketika Irak diserang dengan dalih senjata pemusnah massal dan Libya dijatuhkan atas nama perlindungan sipil, ketiadaan sanksi internasional terhadap AS memperkuat asumsi bahwa kekuatanlah, bukan hukum, yang menentukan legitimasi tindakan global.
Kasus Irak dan Libya berfungsi sebagai uji coba (test case). Reaksi dunia internasional yang lemah—bahkan cenderung pasif—menjadi sinyal bahwa tindakan sepihak dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Dalam teori hegemonic stability, kondisi ini menunjukkan bagaimana hegemon membentuk dan menafsirkan aturan internasional sesuai kepentingannya sendiri. Hukum internasional tidak dihapus, tetapi diterapkan secara selektif: keras terhadap negara lemah, lunak terhadap negara kuat.
Ketika pola ini berhasil, muncul apa yang dapat disebut sebagai ketagihan kekuasaan. Seperti dalam psikologi kekuasaan, keberhasilan tanpa resistensi memperkuat kecenderungan untuk mengulangi perilaku yang sama. AS tidak lagi sekadar mengintervensi kebijakan suatu negara, tetapi bergerak lebih jauh ke arah kriminalisasi personal terhadap kepala negara yang berdaulat. Dalam konteks Venezuela, narasi hukum—misalnya tuduhan pelanggaran HAM atau kejahatan narkotika—berfungsi sebagai legitimasi moral untuk tindakan politik yang sejatinya bersifat hegemonik.
Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui teori normalisasi kekerasan dan intervensi. Ketika tindakan luar biasa (extraordinary measures) dilakukan berulang kali tanpa koreksi institusional, tindakan tersebut berubah menjadi “normal”. Dewan Keamanan PBB yang lumpuh oleh veto, serta ketergantungan banyak negara pada sistem ekonomi dan keamanan AS, menyebabkan absennya perlawanan kolektif. Akibatnya, intervensi terhadap kedaulatan negara tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai bagian dari “tata kelola global”.
Dampak jangka panjangnya sangat serius. Pertama, prinsip kedaulatan negara menjadi relatif dan kondisional. Kedua, preseden ini membuka peluang bahwa siapa pun penguasa negara yang berseberangan dengan kepentingan hegemon dapat mengalami nasib serupa. Ketiga, kepercayaan terhadap hukum internasional semakin terkikis, karena hukum tampak berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai norma universal yang adil.
Dengan demikian, tindakan AS terhadap Presiden Venezuela bukanlah peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari pola struktural dalam sistem internasional yang timpang. Selama tidak ada mekanisme global yang efektif untuk membatasi kekuasaan hegemon, test case semacam Irak dan Libya akan terus melahirkan “ketagihan” baru—dengan Venezuela hari ini, dan mungkin negara lain di masa depan. Dalam kondisi ini, tantangan terbesar dunia bukan hanya melawan intervensi, tetapi memulihkan kembali makna keadilan dan kesetaraan dalam hukum internasional.
Dalam konteks ini, diperlukan keberanian politik negara atau koalisi negara—terutama dari Global South, BRICS, dan Gerakan Non-Blok—untuk memberikan reaksi tegas terhadap praktik sepihak Amerika Serikat. Reaksi tersebut dapat berupa kecaman diplomatik kolektif, penggunaan mekanisme hukum internasional alternatif, hingga penguatan institusi multilateral yang independen dari dominasi hegemon. Tanpa sikap tegas dan terkoordinasi, ketimpangan kekuasaan global akan terus direproduksi dan dibiarkan menjadi norma baru.
(Tulisan ini sudah di muat di Media cetak KR tanggal 21 Januari 2026 )